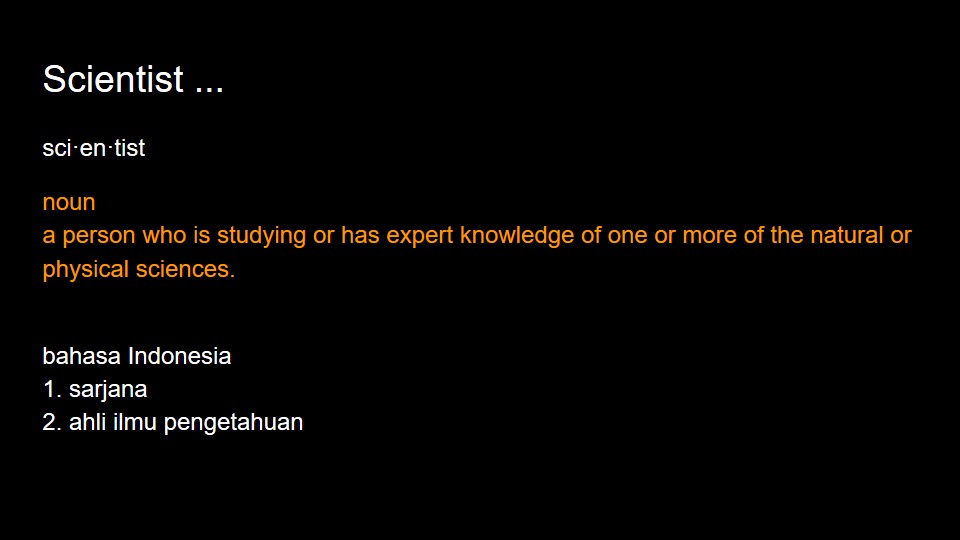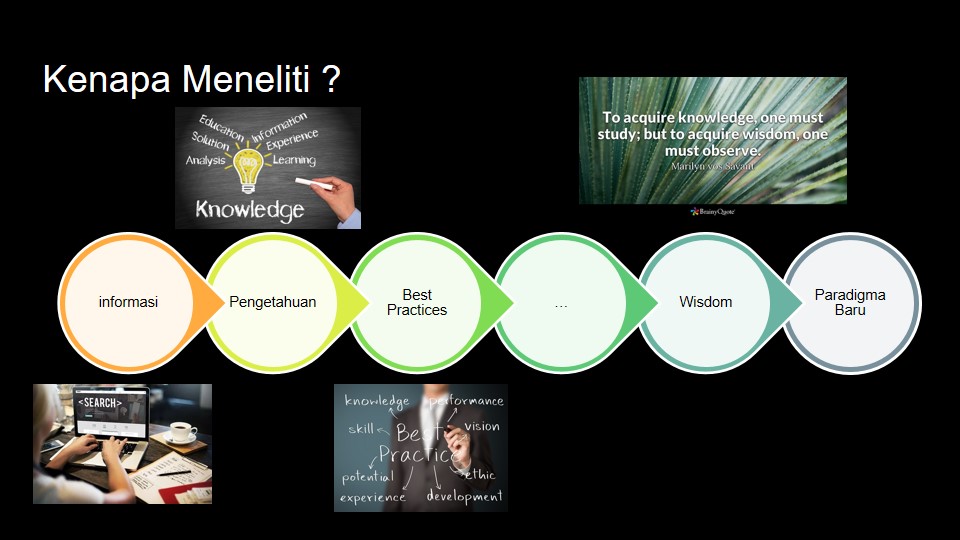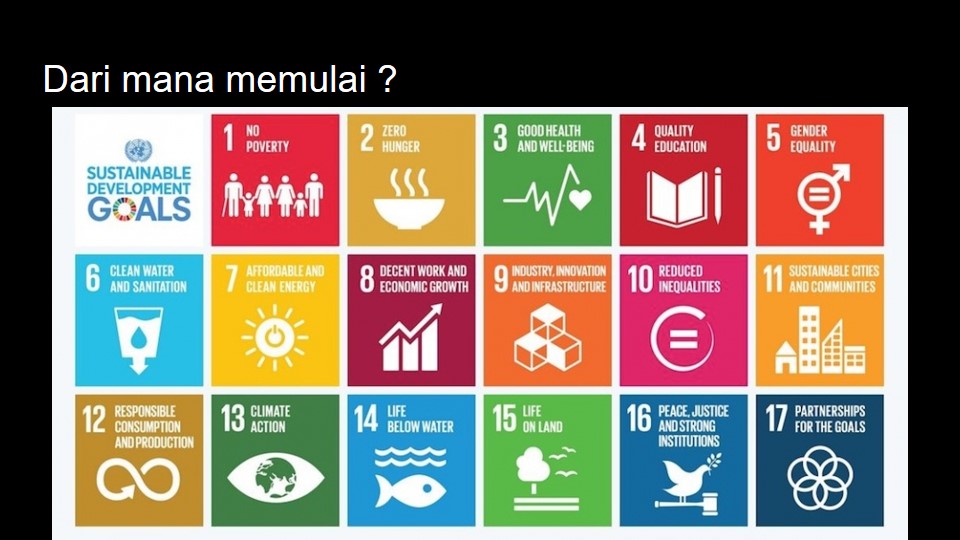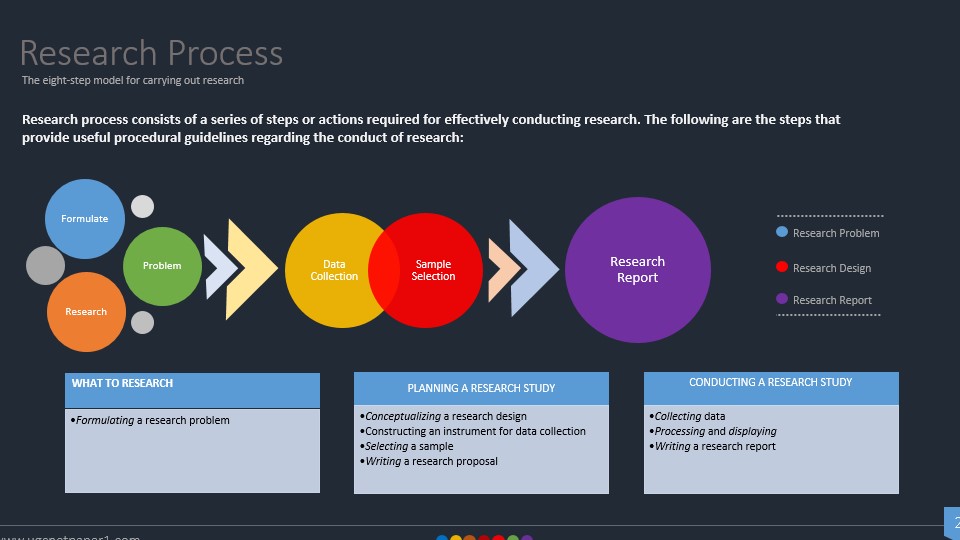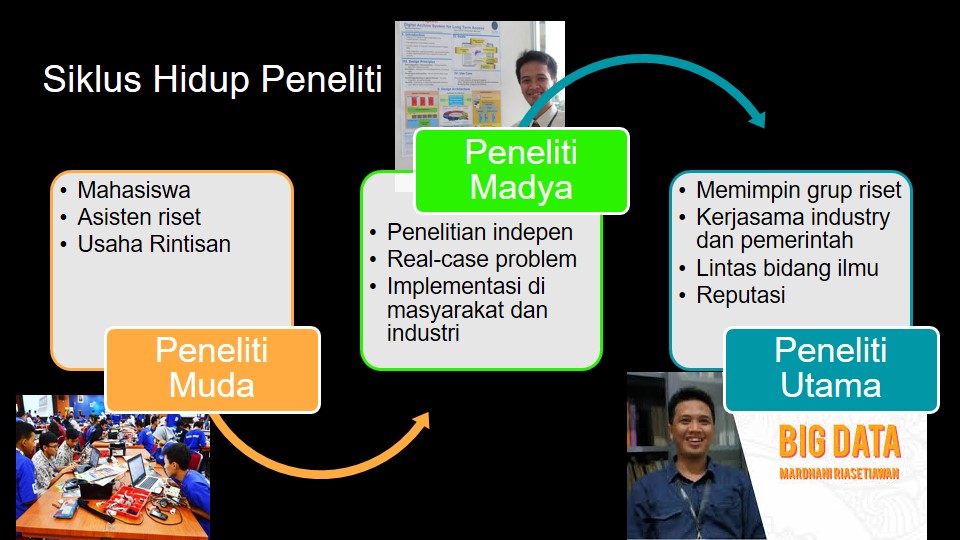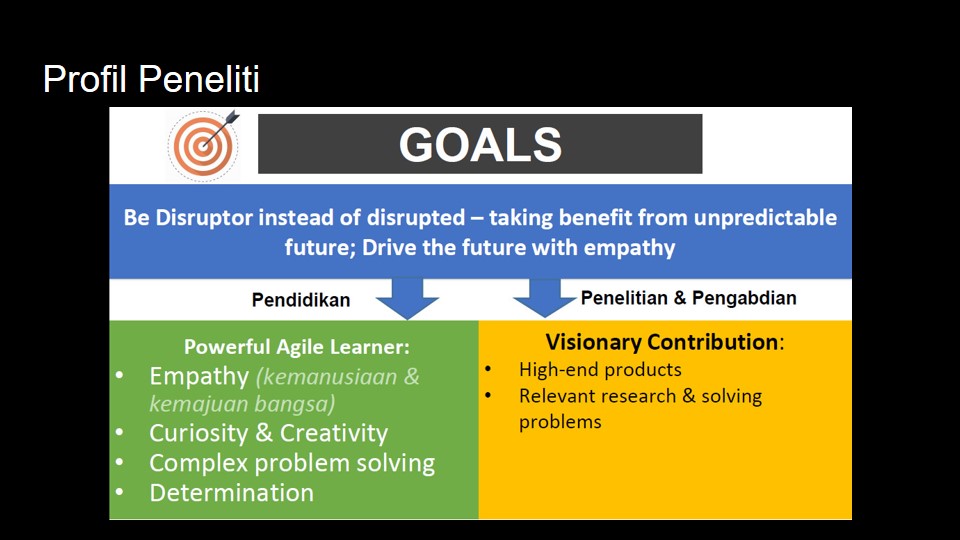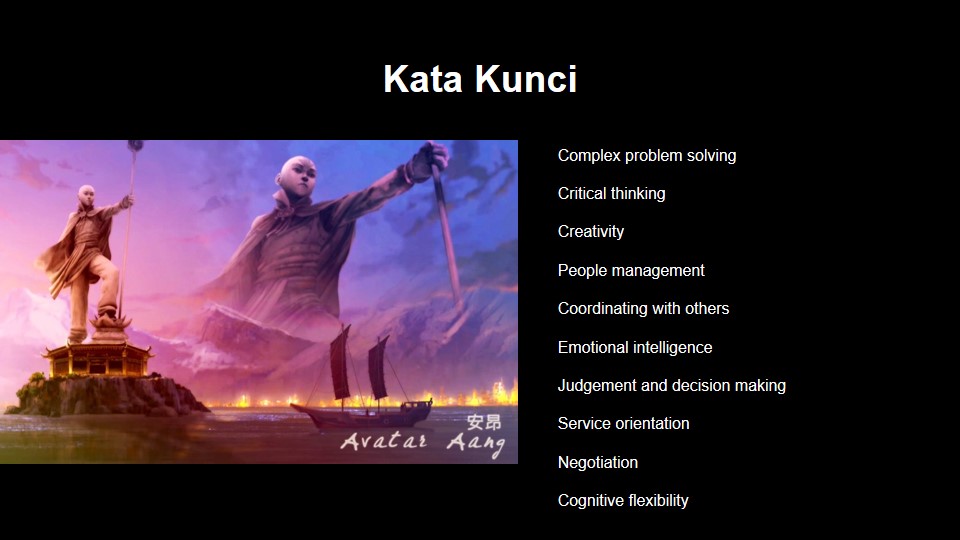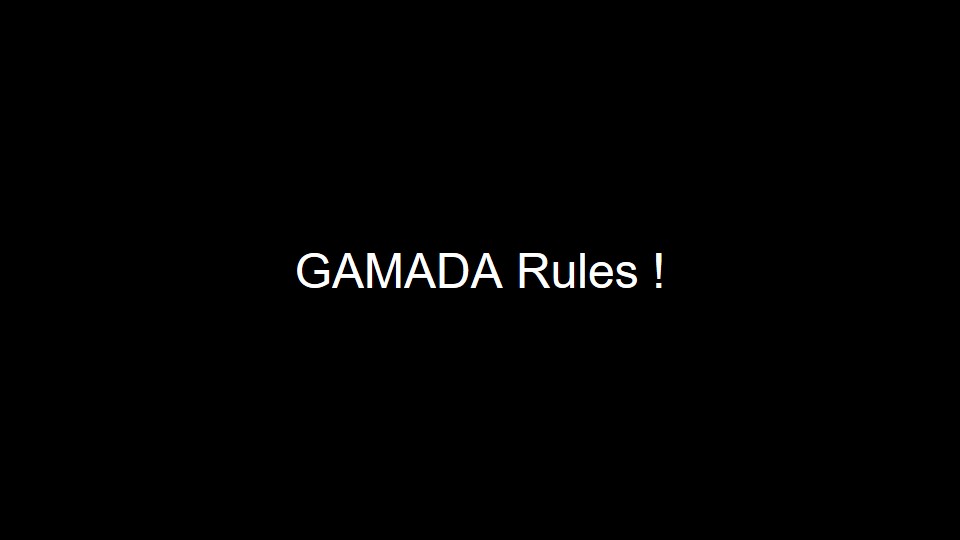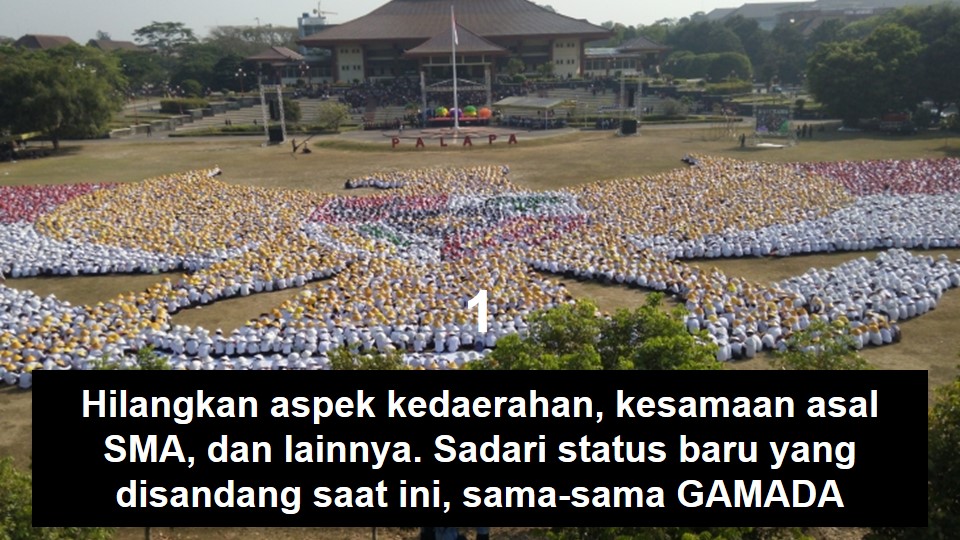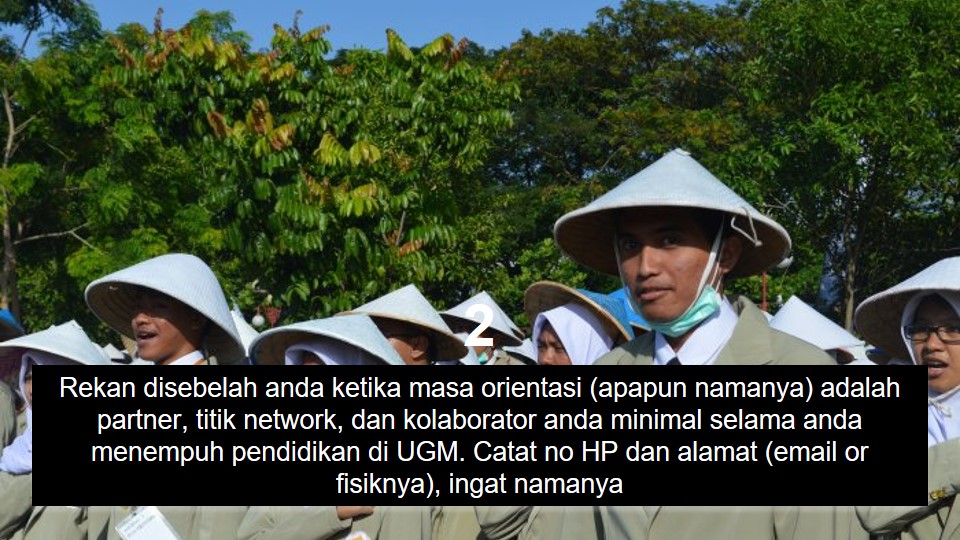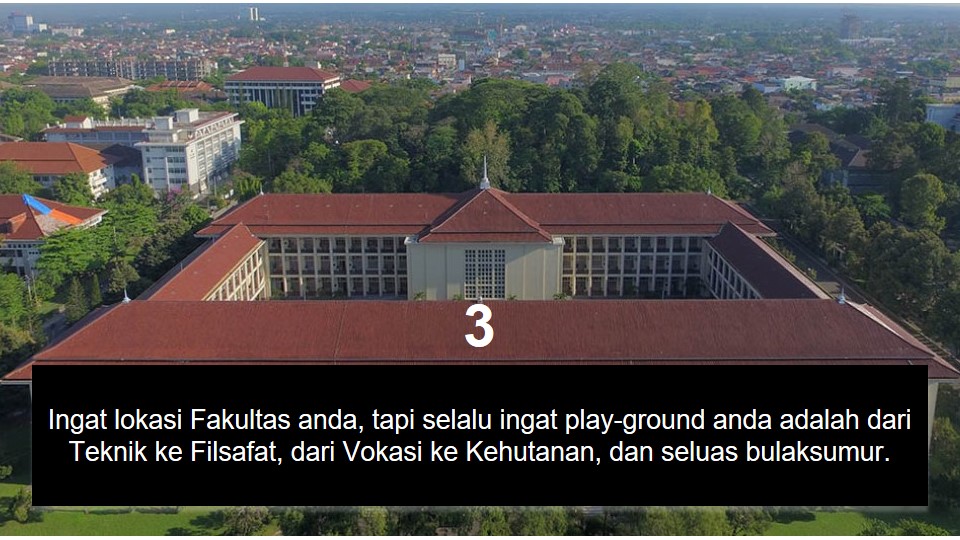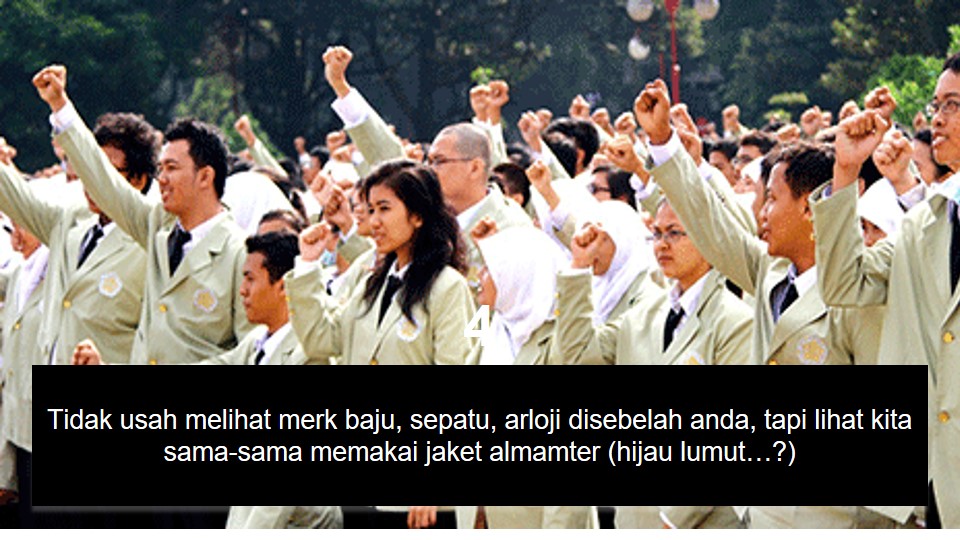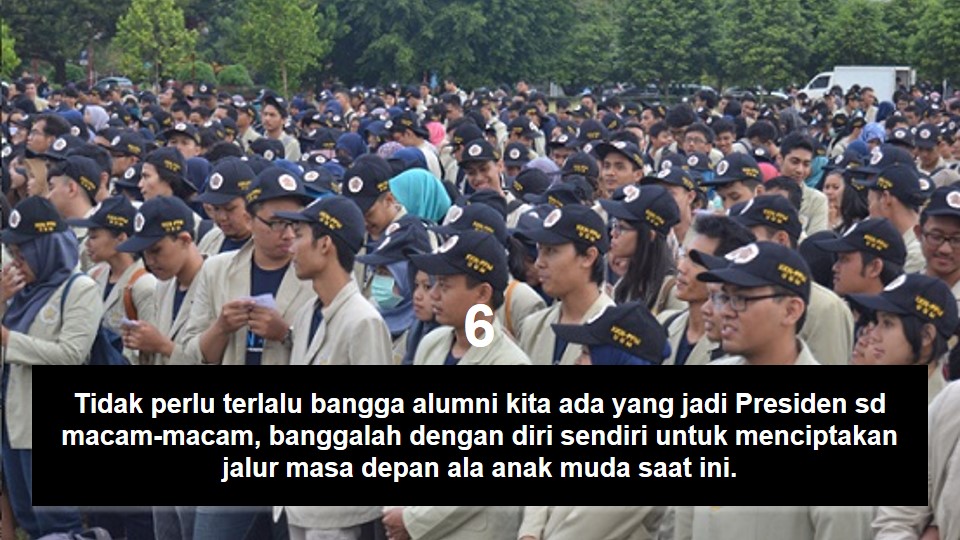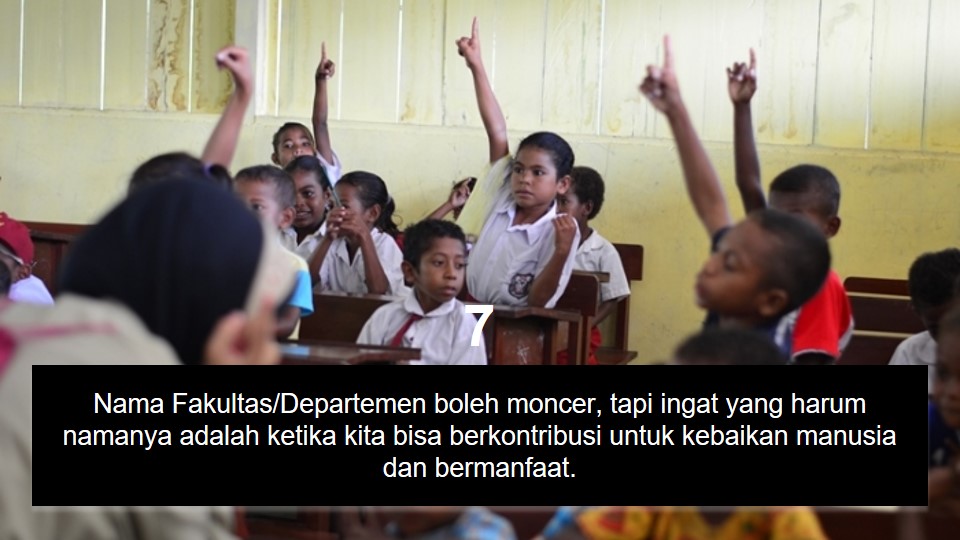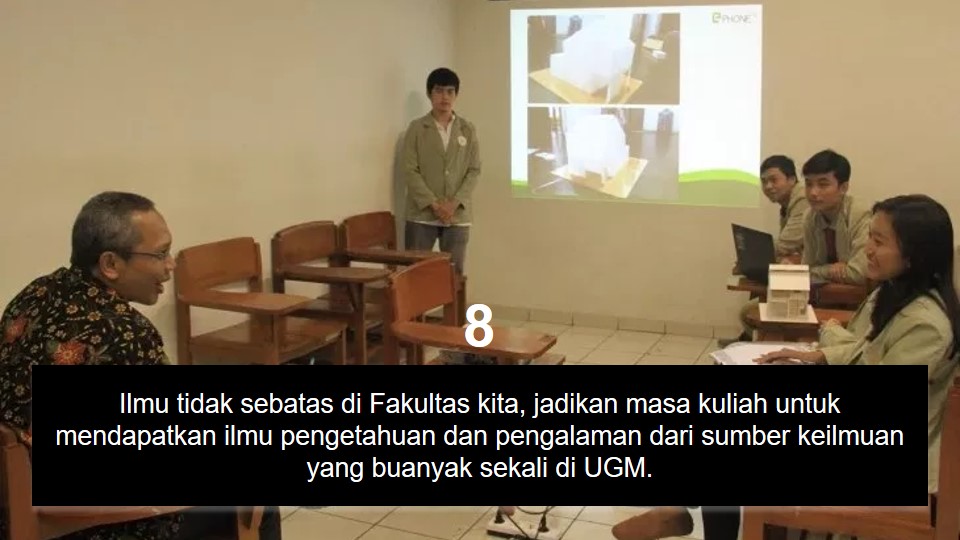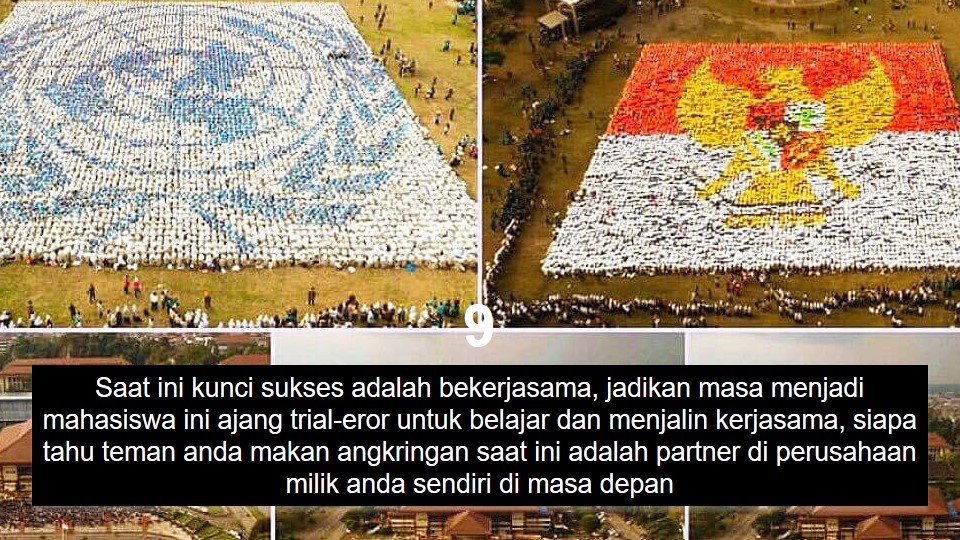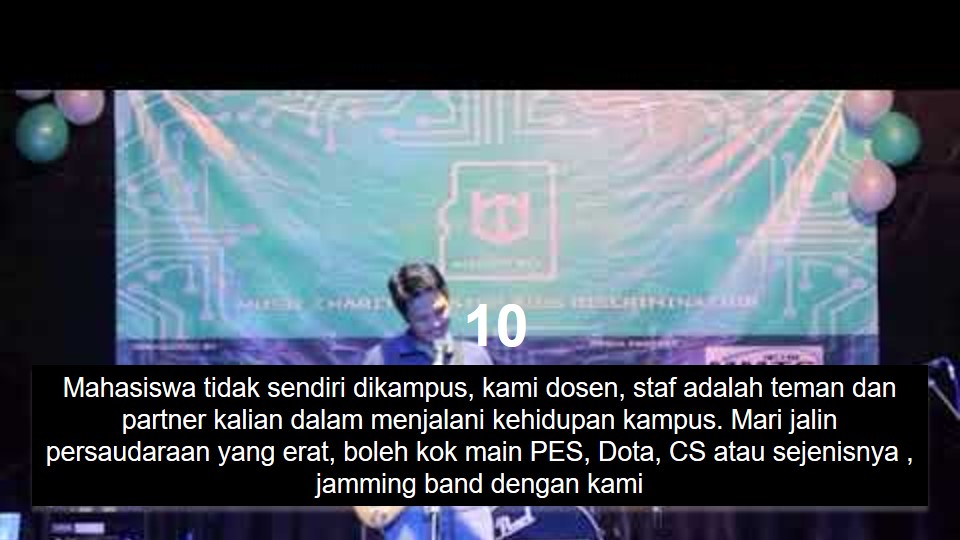Hari ini saya mendapat pengalaman lumayan menarik. Niat awal untuk berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mencari informasi beberapa isu tentang sistem PPDB Zonasi untuk SMP di Yogyakarta. Dari luar kantor terlihat sepi, meja informasi kosong dan disambut petugas keamanan yang membuka pintu dan seorang operator/resepsionis. Mengutarakan niat untuk bertemu petugas informasi, tapi diberi informasi belum siap karena masih melakukan rapat kordinasi. Di saat bersamaan ternyata di dalam sudah banyak sekali orang tua murid dengan wajah muram dan penuh harap, mulai berbicara satu sama lain, bercerita keluh kesah terkait permasalahan PPDB.
Seorang Bapak berbicara agak lantang, mengutarakan bagaimana anaknya tidak bisa mendaftar/diterima di sekolah negeri seluruh Jogja gara-gara jarak rumahnya yang tidak dekat sekolah manapun. Seorang Ibu lebih mengiba lagi karena tidak diterima, dengan komparasi yang diterima ternyata jarak rumah fisiknya lebih jauh dari rumah beliau. Kemudian ada lagi, orang tua yang mengeluhkan minimnya informasi tentang pembagian zonasi dan jarak yang hanya mengandalkan web PPDB dan di update di akhir-akhir (last minute). Kategori prestasi yang awalnya untuk siswa-siswa dengan sertifikat prestasi tertentu, di akhir bisa didaftar untuk yang berdasar nilai UN. Ini hanya beberapa yang tadi cukup keras diutarakan.
Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut, muncul impact yang mungkin bagi Dinas baru disadari, khusus Kota Yogyakarta, terdapat beberapa daerah (kecamatan, kelurahan) yang menjadi wilayah BlankZone, atau daerah yang tidak diterima di SMP manapun hanya karena jarak tadi. Meskipun sistem zonasi ini memang kompetisi jarak terdekat dengan sekolah, saya yakin BlankZone ini baru disadari saat ini. Usaha menunggu pejabat yang berwenang tidak membuahkan hasil. Akhirnya inistaif para orang tua naik keatas menemui pejabat yang ada. Tapi seperti kantor pemerintahan pada umumnya, meja informasi kosong dan jawaban pejabatnya hanya melaksanakan peraturan tanpa penjelasan detail.
Sebagai akademisi saya kok tergugah, dan prihatin. meski mungkin tidak 100% obyektif, karena saya juga menjadi salah satu orang tua yang memiliki kondisi yang sama dengan para orang tua tersebut. Tapi begini, kritik yang ada dibenak saya:
1. Sistem zonasi yang notabene menjalankan peraturan menteri dan lainnya, telah diimplementasikan sangat murni, Saking murninya fokus pada pemerataan, mungkin jargon Pak Menteri sekarang “agar tidak ada sekolah Favorit”. Dan menurut saya tidak berkeadilan. Implementasi ini tidak dibarengi dengan pemetaan anak didik yang mau masuk SMP dan dilihat representasi SMP yang tersedia, sekaligus melihat proposi jarak.
2. Peserta didik yang notabene berjuang mati-matian UN untuk mendapatkan nilai bagus, dirugikan dengan seleksi prestasi yang tidak clear petunjuk dan informasinya, plus pasti akan sulit bersaing dengan jarak di seleksi zonasi.
3. Dinas hanya mengandalkan situs web PPDB dari penyedia layanan untuk mencantumkan semua aturan dan etc, tapi silahkan di cek di yogya.siap-ppdb.com untuk ukuran event besar seperti ini bahkan teknik penulisan aturan main dll-nya tidak tergarap dengan baik. ada fasilitas tanya jawab, tapi dugaan saya hanya dioperatori petugas penjaga social media dengan jawaban standar. Bahkan mungkin keluh kesah disanapun tidak terfasilitasi dengan baik ke pimpinannya
4. Terdapat perbedaan penentuan standar jarak di aturan dengan aturan by sistem. Ini sempat menimbulkan keramaian di hari pendaftaran, meski kemudian bisa terupdate.
Analisis saya akan ada beberapa akibat panjang dari ini:
1. Distribusi siswa yang ke SMP Negeri hanya berdasar banyak tidak akan punya kontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan sejenisnya (karena hanya akan memindah sebagian orang ke bentuk dan wilayah lain). Plus juga tidak akan menghilangkan sekolah favorit dan tidak, hanya menunggu waktu saja sekolah yang kelimpahan siswa dengan akademik baik (misal swasta) akan menjadi sekolah favorit dalam bentuk dan waktu lain…sudah ada contoh di kota lain.
2. Sekolah akan mendapat limpahan siswa sesuai kuota, tapi profil siswa akan sangat random baik secara prestasi akademik, hanya jarak yang homogen. Guru akan punya PR akan sangat banyak u menstandarkan siswa yang luar biasa random profilenya, belum pekerjaan administrasi seabrek lainnya.
3. Ada pihak (bukan konotatif ya) akan mendapatkan keuntungan, sekolah swasta (yang biayanya mandiri) akan mendapat limpahan karena bagaimanapun siswa yang tidak bisa diterima di zonasi akan berpindah kesini. Ya terpaksa orang tua akan memasukan ke sekolah swasta yang baik, tidak peduli dengan jarak juga, Dan tahukan bahwa siswa yang diterima di zonasi hanya separo dari keseluruhan siswa yang masukSMP di Jogja. dan ini akan hanya bergeser saja perpindahan dan mobilisasinya.
Terus bagaimana selanjutnya, karena jawaban standarnya melaksanakan peraturan, meskipun sedih mlihatnya, ketika Presiden kita mendengungkan perubahan, disruptive dan berkeadilan, pola di bawah seperti ini masih model lama. Tapi oke, lets move on, saya mengusulkan seperti ini.
1. Untuk sosialisasi, sudah saatnya intensif menggunakan media sosial, web yang representatif, call center, crisis center, mitigation dan lainnya disiapkan untuk hal-hal seperti ini.
2. Pelaksanaan peraturan seharusnya meniru daerah lain. Beberapa daerah berani (baca: disruptive) dengan mengkombinasikan antara jarak dan batas minimal nilai misalnya, bahkan ada yang berani u menambah daya tampung u memenuhi aspek keadilan jarak dan wilayah.
3. Proses penentuan jarak, wilayah zonasi dan prosedur detail lainnya lebih jauh disampaikan ke sekolah, orang tua siswa. Katanya sudah era e-government yang melayani, mestinya informasi diberikan secara aktif oleh pemerintah, bukan hanya disuruh lihat di web dan sejenisnya.
4. Memperhatikan Blankzone, dan impact lainnya yang akan ini sangat merugikan wilayah-wilayah yang seperti ini, khusus Kota Jogja, analisis data science yang saya lakukan (kalau mau data detail bisa japri), kelurahan warungboto sd Taman siswa dan di pinggir batas kota Jogja menjadi wilayah yang sangat dirugikan. LIhat di web PPDB atau koran hari ini, siswa yang diterima di SMP N hanya berjarak 0 sd 2sekian km. Kota Jogja sendiri luasnya itu atau sumbu lingkarannya itu lebih dari 10 km (pengalaman kalau segosegawe dr kotagede ke UGM).
Terlepas semua itu, tampaknya PPDB sudah selesai, Jogja memang terlalu nyaman untuk hal-hal yang disruptive dan aspiratif sekarang (meski saya masih yakin Yogya bagus u hal-hal kreatif). Saya menulis ini, sekaligus sebagai “pertanggungjawaban publik” karena niat pagi tadi hanya mencari informasi berubah menjadi corong para orang tua yang mencari informasi lebih pasti. Tiba-tiba ditepuk untuk menjadi juru bicara u diskusi dengan entah siapa pejabatnya. Terimakasih untuk Kumparan yang juga memberikan liputan tentang hal ini, semoga ada dorongan untuk diperhatikan oleh stakeholder di Jogja. Terjadi tahun ini, bisa terjadi tahun berikutnya jika tidak ada perubahan.
Sebagai pribadi, saya akan sangat senang dan free untuk berdiskusi dan “speak with data” terutama untuk Dinas jika memang ingin ada perbaikan. Sebaga ortu, kami sudah move on kok, anak-anak kami sudah mulai kami titipkan ke sekolah yang menurut kami baik, semoga kami dan anak-anak kami bisa nanti menjadi pembaharu untuk Jogja yang tidak hanya nyaman tapi juga Baik.
Terlepas dari semua hiruk pikuk, mari tetap berfikir positif, dan move-on saja…dunia tidak berhenti di krn hal ini, semangat carikan solusi masih ada swasta yang baik, luar negeri dan lainnya….
Link liputan dr kumparan : https://m.kumparan.com/…/protes-orang-tua-di-yogyakarta-soa…